
Text
Laut Pasang 1994
Tahun 1994 adalah tahun paling menyakitkan bagiku. Bahkan, bagi warga di kampungku. Kejadian yang tak disangka kehadirannya merenggut banyak senyum dan kebahagiaan.
Aku yang keras kepala dan egois seperti Pada peristiwa 2 Juni 1994, aku mendapat balasan atas semua perbuatanku. Malam itu riuh suara air naik dengan cepat ke daratan, teriakan, jeritan, dan reruntuhan barang yang saling berbenturan. Aku bersusah payah meneriaki satu persatu nama ketujuh anakku hanyut diempas air malam itu. yang dicambuk oleh takdir.
Entah sebuah keberuntungan atau justru kesialan. Aku selamat dari peristiwa itu. Sebuah tiang besar menjadi tumpuanku menyelamatkan diri dari kuatnya dorongan air yang semakin naik.
Mataku menerawang jauh ke berbagai penjuru, meski yang kulihat hanya mayat yang terapung dibawa arus. Semua terlihat gelap karena listrik padam. Beruntung cahaya bintang masih sudi memberikan sedikit cahayanya untuk manusia sepertiku.
Di bawah langit malam, tubuh ini sudah kehabisan tenaga. Manusia egois sepertiku hanya bisa menangis menyesali perbuatan pecundang yang telah aku jalani bertahun-tahun. Anak-anakku tidak ada yang pulang satu pun, meski aku sudah berusaha untuk tetap membuka mata, mereka tidak pernah datang. Suaraku nyaris habis, hanya sahutan gemuruh air yang terdengar seperti ledekan di telingaku. Mereka sedang menertawakan sosok Bapak brengsek yang tengah menyesali perbuatannya.
Kalau ditakdirkan untuk merasakan kehilangan yang kedua kalinya, aku jelas lebih memilih ikut mati daripada harus bertahan dan hidup dalam kesengsaraan. Melanjutkan hidup tanpa anak-anak di sampingku sama dengan hidup tanpa nyawa.
Jika sampai terbukti tidak ada yang selamat, aku memohon pada Tuhan untuk cabut saja nyawaku sekarang.
Aku benar-benar menyesal setengah mati. Menyesal karena belum sempat meminta maaf pada mereka.
Apa harus dengan cara seperti ini kalian semua menghukum Bapak? Bapak menyesal, nak. Bapak minta maaf.
Sinopsis di cover belakang:
Peristiwa yang menghancurkan seluruh kota dalam waktu singkat.
Tujuh raga paling menyedihkan menjadi saksi bagaimana gilanya gelombang pasang malam itu. Malam terakhir penuh bintang, seindah senyuman ibu enam tahun silam.
"Apta! Esa! Pegang tangan Mas yang kenceng!"
Kalimat itu menjadi kalimat terakhir Khalid sebagai usahanya yang ternyata sia-sia. Semuanya terjadi begitu cepat, air laut naik kepermukaan lebih ganas dari dugaannya dan mampu memisahkan genggaman tangan mereka satu sama lain tanpa belas kasihan.
"Bagaimanapun takdirnya nanti, tujuh ya akan tetap tujuh. Ingat kata Si Mbah, kalau kita itu satu, satu jiwa yang terbagi di tujuh raga berbeda."
Ketersediaan
Tidak ada salinan data
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
P7001813 LIL L
- Penerbit
- DEPOK : PT Tekad Media Cakrawala.,
- Deskripsi Fisik
-
320 hlm; 14 x 20 cm
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
9786235953366
- Klasifikasi
-
813 LIL L
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
-
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
-
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar
 Karya Umum
Karya Umum  Filsafat
Filsafat  Agama
Agama  Ilmu-ilmu Sosial
Ilmu-ilmu Sosial  Bahasa
Bahasa  Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Murni 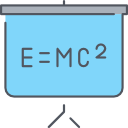 Ilmu-ilmu Terapan
Ilmu-ilmu Terapan 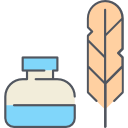 Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 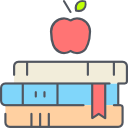 Kesusastraan
Kesusastraan  Geografi dan Sejarah
Geografi dan Sejarah